Membaca Realitas atas Kuasa Fotografi *
Judul Buku : Literasi Visual Manfaat dan Muslihat Fotografi
Penulis : Taufan Wijaya
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Edisi : I, 2018
Tebal : xxxiii+ 97 Halaman
Buku ini mencoba memberikan gambaran betapa pentingnya literasi visual dalam fotografi.
Tak banyak perbincangan fotografi di luar perkara teknis. Perbincangan seputar perangkat, tip dan trik masih mendominasi, baik dalam majalah, buku, maupun obrolan-obrolan dalam komunitas foto.
Agak sedikit berbeda dengan film, seni rupa, maupun sastra yang sudah demikian kompleks perbincangannya. Lantas pertanyaannya, apakah perbincangan fotografi hanya berorientasi pada kerja-kerja teknikal? Dan abai pada literasi dan kajian-kajian fotografi?
Setidaknya, sejak awal 2000-an perbincangan mengenai wacana fotografi mulai muncul, meski tak banyak. Kali ini Taufan Wijaya melalui buku Literasi Visual; Manfaat dan Muslihat Fotografi memperkaya bacaan dalam ranah wacana visual. Ia mencoba memberikan gambaran betapa pentingnya literasi visual dalam fotografi.
Buku setebal 97 halaman itu membuka keran pemikiran yang selama ini tersendat dan bagi beberapa kalangan dianggap “merumitkan” dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan.
Pada bagian pengantar, Taufan mulai dengan meminjam terminilogi Mc Luhan (1967) tentang bagaimana teknologi berperan penting dalam mengubah kebiasaan orang dalam keseharian. Dalam konteks fotografi ini menarik, kita bisa menyaksikan bagaimana melalui perangkat kamera seseorang mampu mengonstruksi realitas yang ada.
Selanjutnya fotografi mampu menempatkan dirinya, bukan sekadar sebagai penanda kelas sosial. Pada bagian itu, Taufan memaparkan bagaimana fotografi mampu merespon fenomena sosial yang ada.
Dia mencontohkan foto di Venue Pencak Silat Asian Games 2018 Rabu (29/8) saat pesilat Hanifan Yudani Kusumah mengajak Presiden Jokowi dan rivalnya di pemilihan presiden, Prabowo Subianto berpelukan bersama. Juga foto ledakan bom di lomba Marathon Boston 15 April 2013, dan foto Alan Kurdi, bocah pengungsi asal Syriah yang tenggelam.
Contoh-contoh tersebut menunjukan bagaimana fotografer dengan daya literasi yang memadai mampu merespon fenomena yang ada untuk dihadirkan kepada publik. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaiman publik menafsir foto yang muncul? Apakah literasi visual diperlukan?apakah literasi visual hanya kebutuhan para penggguna perangkat kamera?
Dalam praktiknya, fotografi menyoal relasi antara fotografer-institusi-karya foto-audiens. Pada salah satu paragraph di bagian pengantar buku ini dapat kita jumpai bagaimana kekuasaan memiliki peran yang cukup penting dan patut mendapat perhatian dalam fotografi. “Menurut pendekatan Michel Focault, kekuasaan yang tampil dalam fotografi tidak berada dalam foto itu sendiri, tapi dilekatkan dan bergantung kepada siapa yang menggunakannya”(hlm. Xix).
Dengan menempatkan perspektif dari Foucault, saya rasa pembahasan dalam buku ini semakin kompleks dan menarik. Dengan kata lain relasi kuasa yang muncul mengakibatkan fotografi dan perangkatnya menjadi sesuatu yang tidak netral dan tidak alamiah karena “bergantung kepada siapa yang menggunakannya”.
Rasanya, melalui pengantar buku ini, Taufan hendak membangun pemahaman sekaligus membuka obrolan-obrolan lebih dalam soal literasi visual. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa terjawab dengan membaca buku ini sampai tuntas.
Pada bab ketiga “Melihat Foto”, terdapat dua tulisan dengan judul Penglihatan Kritis dan Semiotika Roland Barthes. Jika kita mengacu pada konsep pembacaan foto ala Roland Barthes, antara membaca dan melihat memiliki tahapan yang berbeda. Barthes mengajukan tiga tahap dalam membaca foto: Perseptif, Kognitif, Etis ideologis. Dan Barthes juga mengajukan Tiga tahap pengalaman melihat sebuah foto: Pengalaman memilih atau memperhatikan foto tertentu, Pengalaman tertarik pada unsur-unsur tertentu, dan Tahap pengalaman paling menyentuh ke dalam diri.
Selanjutnya, bab terakhir buku ini membahas mengenai Etika Fotografi yang di dalamnya disoal dua hal, yakni manipulasi dan kesopanan. Bila mengacu pada etika dalam jurnalisme, dalam pemotretan saja narasumber (subjek) berhak menolak untuk difoto, dan sebagai penghormatan, semestinya fotografer tidak memaksakan untuk bisa memotret (hlm.68).
Di saat kamera menjadi perangkat “kuasa” fotografer dalam membingkai realitas, maka ada etika yang harus dipatuhi. Etika semacam inilah yang acapkali diabaikan, dan tak banyak khalayak yang paham betul mengenai etika dalam fotografi. Juga atas keterlibatannya dalam praktik fotografi, seorang subjek foto, model, maupun narasumber alangkah idealnya jika melek visual, memahami literasi visual.
Di tengah sepinya perbincangan wacana fotografi beserta literasi di dalamnya, kehadiran Buku Litersi Visual; Manfaat dan Muslihat Fotografi menjadi semangat baru dalam perbincangan fotografi, dan diharapkan mampu membuka diskusi-diskusi lebih lanjut perihal fotografi di Indonesia.
*Resensi ini pernah dimuat di Jawa Pos, Minggu 6 Januari 2019, Halaman 4
Tiga Titik dalam Fotografi: Teori, Kajian, dan Sejarah Foto
Setiap berkunjung ke toko buku, Saya selalu menyempatkan untuk mencari atau sekadar melihat-lihat buku-buku fotografi melalui komputer. Tak banyak yang saya temukan. Sebagian besar, buku-buku foto yang saya temukan didominasi oleh buku-buku yang membahas bab teknik maupun tips dan trik. Sekilas terasa biasa saja, mengingat Indonesia menjadi salah satu tempat tumbuh suburnya industri visual bernama fotografi. Fotografi bukan lagi barang mahal. Siapapun bisa mendapatkan kamera, siapapun bisa memotret, dan siapapun bebas mengunggah karya foto ke media yang dimiliki. Saling bertukar tips menjadi hal yang lumrah dan jamak kita temui di perbincangan seputar fotografi.
Namun apakah akan selamanya fotografi hanya membicarakan bab yang demikian? Tentu saja jawabnya bisa panjang, bisa pendek. Bisa rumit, bisa juga sederhana. Jawaban sederhanya: Perbincangan mengenai bab teknik perlu dilakukan dalam proses kreatif menciptakan sebuah karya. Lantas setelah foto itu jadi? Sekadar dikonsumsi kah? Setelah dikonsumsi? Lantas, apakah dalam olah visual tidak ada wacana-wacana sosial yang mempengaruhi? Apakah ketika produk visual (foto) itu jadi akan berdiri sendiri dan bebas nilai? Nah, jawaban yang tak sederhana akan muncul dari pertanyaan terakhir yang saya tuliskan tersebut.
Buku Photo Story; Panduan Membuat Foto Cerita karya Taufan Wijaya yang akan kita perbincangkan ini menarik. Dalam hal ini, saya lebih ingin menempatkan buku ini dalam perbincangan mengenai teori dalam fotografi. Jika kita runut ke belakang, fenomena dalam arena fotografi sangatlah kompleks. Fotografi mampu secara tajam mengkonstruksi realitas, dan dalam beberapa hal berfungsi sebagai kontrol sosial. Fotografi juga menjadi pertanda kemeriahan pesta-pora modernisasi. Gampangnya, fotografi hadir sebagai simbol masyarakat modern. Sayangnya, fenomena semacam ini tidak diimbangi dengan keberadaan buku-buku teori. Kita seolah terjebak pada sesuatu yang teknis, dan abai pada definisi-definisi dan pengertian mendalam mengenai foto itu sendiri. Ketika teknologi semakin berkembang dan genre-genre dalam fotografi juga terus berkembang, tapi tidak diimbangi dengan “sebuah” pegangan dan patokan yang jelas, jangan-jangan selama ini, mereka di luar sana (para pegiat kamera) hanya melakukan sesuatu yang –mereka anggap menyenangkan- tapi tidak bisa menjelaskan apa yang telah mereka produksi. Fenomena semacam ini tentu saja bukan kabar yang menggembirakan bagi fotografi Indonesia. Di sinilah buku teori itu perlu dihadirkan.
Melalui teori kita dapat melakukan kajian terhadap suatu karya foto. Teori muncul karena telah diadakan pengamatan terhadap objek visual, dan teori dapat berkembang sesuai perkembangan fenomena fotografis yang ada. Hubungan antara teori, kajian, dan sejarah dalam arena fotografi tidak bisa dipisahkan. Dengan melakukan kajian, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penyusunan sejarah juga perkembangan teori yang ada dalam fotografi. Sebaliknya, kajian bukan hanya saja memerlukan teori, namun juga –dalam beberapa hal- memerlukan referensi dari sejarah sebagai titik berangkat.
Saya ingat salah satu buku foto karya Olivier Johannes Raap: “Soeka Doeka di Djawa Tempo Doeloe”. Buku tersebut berisi ratusan kartu pos dengan objek foto masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Uraian-uraian yang ia sampaikan mampu menyusun dan melakukan kategori atas foto-foto yang ada pada waktu itu. Contoh lain bisa kita dapati dalam buku yang sedang kita bahas ini. Dalam salah satu bagiannya, Taufan melampirkan foto cerita “Jakarta Masa Lalu” di harian Kompas edisi Minggu 29 Juli 2012 karya Agus Susanto. Juga bisa kita dapati pada halaman 26, mengenai foto cerita “ Sang Instruktur” yang dimuat dalam majalah Readers Digest Indonesia Edisi Desember 2006. Karya-karya foto tersebut, selain menampilkan visual juga mampu menyusun hadirnya sejarah foto indonesia. Selain mampu menyusun sejarah pada genre foto cerita, foto-foto tersebut juga memuat wacana visual yang berkembang pada waktu itu.
Sebagai buku teori, buku karya Taufan Wijaya ini berusaha melakukan definsi serta batasan dan aturan main dalam membuat sebuah foto cerita. Tentunya literasi seperti ini perlu sebagai panduan dalam penyusunan karya dan sebagai acuan dalam pengkajian fotografi. Dengan adanya teori kita bisa memahami alur penceritaan serta bagaimana foto itu disusun. Dalam prakatanya, Taufan mengutarakan bahwa banyak fotografer menemukan foto cerita di koran atau majalah dan menganggap semua bentuknya sama. Padahal foto cerita disajikan dalam tiga bentuk umum, yaitu deskriptif (descriptive), naratif (narrative), dan foto esai (photo essay)
Masing-masing dari bentuk tersebut memiliki corak khas serta memiliki titik poin penekanan yang berbeda. Pola-pola penceritaan membutuhkan kekuatan wacana. Mirip-mirip ketika kita membuat karya sastra, entah puisi, cerpen, maupun novel. Kekuatan unsur instrinsik dan ekstrinsik tentu saja diperlukan.
Selanjutnya, mengomentari satu yang khas dan “mutlak ada” dalam foto cerita: keberadaan teks. Teks mampu meningkatkan daya penceritaan sebuah foto. Barthes, pernah menuturkan mengenai peran kata terhadap gambar amatlah penting, ia menggunakan istilah pengait/jangkar ( achorage) untuk menggambarkan fungsi kata-kata untuk menjadi narasi. Barthes berpendapat bahwa gambar visual bersifat polisemi dan kata-kata membantu “menetapkan” atau dengan kata lain mengarahkan terhadap pembacaan. Inilah yang kemudian oleh Stuart Hall (1973) disebut sebagai “a preferred reading”. Kata-kata membimbing/mengarahkan terhadap pemaknaan sebuah foto. Hubungan antara teks dan visual bersifat resiprokal, keduanya saling terikat juga saling mendukung dalam pembentukan makna. Keberadaan keterangan foto (caption) adalah sesuatu yang penting, ia bukan saja akan berdaya dalam memberikan pengarahan, namun juga mampu membangun konstruksi, karena tekslah yang kemudian memunculkan/melengkapi informasi mengenai fakta-fakta (sosial) yang tidak muncul dalam sebuah foto. Melalui tekslah kita akan mendapati fakta sosial secara utuh. Teks menguatkan materi visual sekaligus mengarahkan pada pembacaan yang lebih sahih.
Sebagai penutup, bahwa fotografi bukan sekadar urusan menekan tombol shutter, fotografi lebih dari sekadar perangkat kamera. Pengamatan wacana visual, serta pemahaman teori perlu dilakukan. Teori mampu memberikan kemudahan untuk memahami objek. Akan tetapi, yang perlu kita ingat, bahwa teori bukanlah sesuatu yang “tetap”. Bukankah tidak ada teori yang betul-betul lengkap?, selalu ada celah dan ia (teori) selalu membutuhkan perbaikan terus menerus sesuai perkembangan fenomena yang ada. Tentunya dengan hadirnya buku ini (Photo Story; Panduan Membuat Foto Cerita ) telah menghidupkan literasi dalam fotografi dan membuka wacana serta mampu membangkitkan perbincangan yang lebih menarik lagi seputar fotografi. Salam.
* Catatan ini digunakan sebagai modal diskusi buku “Photo Story; Panduan Membuat Foto Cerita” Karya Taufan Wijaya. (Jakarta: Gramedia, 2016). Di selenggarakan di FSR ISI 15 Oktober 2016
Memoar Fotografis: Memperbincangkan Retorika Visual Fotografis dalam 44 Tahun
karena tak ada foto yang “benar-benar” bisa bicara. Namun, melalui materi visual yang termuat di dalamnyalah kita bisa membicarakan sebuah foto dengan ragam perspektif.
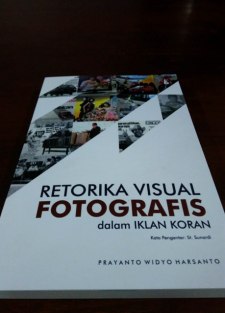
Rentang waktu 44 tahun menjadi rentang yang cukup panjang dalam memperbincangkan fotografi dan iklan. Jika biasanya memoar mengacu pada catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang, maka tidak dengan catatan ini. Catatan ini sengaja saya beri judul “memoar fotografis” dengan pertimbangan bahwa buku ini melibatkan peristiwa fotografis iklan koran dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dimulai dari iklan cetak pertama di Surat Kabar Kompas (1965) hingga 2009. Baik iklan maupun fotografi, keduanya sama-sama berangkat dari fenomena sosial. Secara sosiokultural keduanya bisa dikatakan sebagai bentuk respon kebutuhan, baik kebutuhan industri maupun kebutuhan masyarakat.
Ada 437 iklan yang menjadi amatan Prayanto W.H, penulis buku ini (baca: Retorika Visual Fotografis dalam Iklan Koran). Jumlah yang banyak, bahkan dapat dikatakan sangat banyak. Selama periode tersebut, iklan-iklan dikategorikan. Kategorisasi tidak sebatas pada bab kerja-kerja mekanis, namun juga hal-hal politis dalam fotografi.
Sebagai arena multidisiplin, fotografi dalam berbagai bidang (termasuk fotografi dalam iklan) bisa dibicarakan dengan ragam keilmuan. Yang kemudian menarik untuk diperbincangkan di awal adalah perihal persinggungan fotografi dengan industri. Sejak awal kemunculannya, fotografi menjadi salah satu bentuk penemuan yang cukup penting dalam merespon kebutuhan manusia dan industri. Terlebih lagi, ketika fotografi ditemukan dan dipatenkan pada 1839, di Eropa sedang terjadi Revolusi Industri. Dimana alur perdagangan kian padat, dan pabrik-pabrik semakin bermunculan. Dan fotografi muncul sebagai salah satu kekuatan visual (baru) dalam merespon tumbuh kembangnya industri pada waktu itu.
Menyoal Retorika Visual, merujuk tulisan Matthew Rampley dalam Exploring Visual Culture (2005) yang berjudul Visual Rhetoric. Di katakan bahwa Retorika visual memiliki peran penting dalam melihat budaya visual dalam kaitannya dengan mekanisme sosial dan ideologi. Dalam salah satu sub babnya: Visual Communication and Visual Rhetoric, Rampley “meminjam” salah satu esai Barthes yang membahas sampul majalah Paris Match. Sampul tersebut menampilkan seorang prajurit kulit hitam dengan seragam militer Prancis sedang memberi hormat kepada Bendera Prancis. Esai ini digunakan untuk menjelaskan relasi (kuasa) antara produk visual dengan struktur sosial yang ada. Visual semacam ini memiliki daya “politis” dalam membangun opini serta membangun “kesadaran” audiens. Pun dalam bahasan ini (fotografi iklan). Iklan melalui fotografi dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga mampu membangun tawaran yang “ideal” mengenai kehidupan. Tawaran “ideal”, atau lebih jauh bisa dikatakan seolah-olah “ideal”. Kata ideal sengaja saya kasih tanda petik, karena “ideal” tentu saja bukan sesuatu yang serta-merta muncul dalam benak konsumen, tapi melalui proses pemaknaan yang kompleks. Ada relasi kuasa antara Industri (pembuat iklan) dan (calon) konsumennya.
Sependek yang saya tahu, tak banyak buku-buku yang membincangkan fotografi dari sisi wacana kritisnya. Kebanyakan hanya berpijak pada persoalan teknis. Dan tak banyak para mahasiswa yang mengambil tugas akhir bab fotografi mau mengalih mediakan dari format akademis (skripsi-tesis-disertasi) ke dalam format buku yang lebih lentur. Buku yang sedang kita bahas ini merupakan “alih format” dari disertasi ke dalam bentuk buku, dan menjadi salah satu dari yang sedikit tersebut. Hal ini tentu saja membawa angin segar dalam perbincangan fotografi yang “hampir selalu” berorientasi dalam persoalan teknis.
Secara pragmatis, fotografi dalam iklan berfungsi untuk mempengaruhi konsumen, namun dalam keparagmatisannya ada sesuatu yang politis. Bukan hanya sekadar mendaya fungsikan kemapanan estetika, namun ada “tawaran ideal” bagi kehidupan sosial. Di sinilah kemudian fotografi mampu membangun konstruksi aneka rupa kode sosial mengenai sesuatu yang “ideal”. Nilai-nilai “ideal” tersebut kemudian –dalam bahasan ini, salah satunya- diperantarai melalui figur tokoh sebagai pembawa pesan.
Setidaknya ada dua hal yang menarik untuk kita perbincangkan dalam buku ini, yang pertama menyoal kekuatan fotografi dalam mengkonstruksi realitas, baik dari segi teknis maupun wacana (materi) visualnya. Yang kedua: mengenai citra-citra periklanan di setiap periodenya. Penulis membagi tiga periode dalam kajiannya. Dan masing-masing periode menunjukan gaya visual serta wacana yang berbeda. Tidak semua bab akan saya bicarakan dalam ulasan kali ini, hanya beberapa saja. Terutama bagian-bagian yang mengacu pada gaya fotografi dan wacana-wacana (politik) fotografis. Meski tidak menutup kemungkinan bagian-bagian lain bisa saja disinggung, karena pertautan dalam masing-masing bab bisa dibicarakan secara mandiri maupun secara bertaut.
Tiga periodisasi masa dalam buku ini; yang pertama periode 1965-1970an. Pada periode ini iklan-iklan menggunakan kekuatan visual fotografi untuk membangun citra produk. “gaya informasi iklan bersifat informasi yang berorientasi pada produk” (hlm: 98). Beberapa di antaranya: Iklan pertunjukan musik The Trolls Quartet (10 September 1965), Iklan Corned Beef Chips (23 Juni 1967), dan Iklan Electone merek ‘Yamaha’ (27 Juni 1976). Jika dilihat dari visualnya, pada lapisan lebih dalam, Iklan-iklan pada periode ini selain berorientasi pada produk juga membawa tawaran mengenai gaya hidup. Ada konstruksi identitas yang diprasaranai oleh pakaian. Juga ada “identitas” figur yang didayakan untuk mendongkrak pemasaran. Misalnya pada iklan Corned Beef Chips, terdapat teks yang secara jelas mengacu pada hidangan “saya selalu memakai CIP Corned Beef & Sopini untuk membuat bermacam-macam hidangan yang lezat” (hlm: 104). Dengan bintang iklan Ny. Tanzil yang mengenakan sanggul dan kebaya. Ini menarik, bagaimana hidangan “ala barat”, namun dalam iklan disajikan oleh seorang yang bersanggul dan berkebaya yang notabene “corak budaya timur”. Ada semacam “permainan” identitas dalam iklan tersebut.
Selanjutnya pada periode kedua: 1980-1990-an, ada citra diri yang difungsikan sebagai kekuatan iklan. Citra beserta identitasnya dikonstruksikan sebagai pola wicara dalam iklan. Beberapa iklan yang menjadi ulasan dalam periode ini: Iklan Sabun Lux ( 9 maret 1978), Iklan televisi ‘Grundig’ (22 Januari 1980), Iklan Rexona ( 6 Juni 1980), Iklan Mobil ‘Kijang’ (10 Desember 1986) dan iklan Mobil Mazda (11 November 1995). Permainan metafor (visual) terlihat dalam periode ini. Teks didayakan untuk membangun imaji yang ideal. “ Saya pertama kali mengenal LUX di Paris”, Teks ini muncul dalam Iklan Lux. Tampilan foto seorang wanita berdandan ala wisatawan, dengan latar belakang Menara Eiffel. Modis. Sesuai dengan apa yang selama ini diidentikan dengan Paris sebagai kota yang modis. Selanjutnya, pada Iklan Rexona: “Akhirnya dia yakin berkat Rexona”. Visualisasi sepasang –mungkin- kekasih, berdiri berdekatan dengan perempuan sedang asik dan lelakinya terlihat melirik dengan senyuman kecil.
Periode ketiga; pasca 2000an, gaya visual iklan mulai bergeser pada ekspresi pengalaman pengguna. Secara sosial, ekspresi pengalaman masyarakat didayakan dan dijadikan sebagai strategi dalam konstruksi visual iklan. Seperti terlihat pada Iklan Sepeda Motor ‘Dast’ ( 1 November 2000), Iklan pendingin ruangan merek Sharp (24 Juli 2009), Iklan Flexi (13 juni 2009) dan Iklan Handphone Samsung (13 Mei 2002).
Dari rangkaian data dan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa visualisasi fotografis dalam iklan menjadi representasi kehidupan industri dan kehidupan masyarakat (konsumen) yang berorientasi pada tawaran “ideal”. Buku ini cukup komplit dalam membincang fotografi dalam iklan, tapi bukan berarti lantas menutup kemungkinan untuk membicarakan hal yang sama (fotografi dalam iklan). Karena ketika sebuah objek sudah atau sedang diperbincangkan, sekomplit apapun, tentunya akan terus melahirkan turunannya, celah-celah itu tetap tersedia dan perlu untuk terus diisi. Dan di sinilah menariknya. Ketika teknologi makin berkembang, terlebih lagi dengan kehadiran ruang media baru, fotografi dengan gaya visualnya pun terus berkembang. Tentu saja kehadiran buku ini bisa menjadi semacam alat berpijak dalam melihat fenomena fotografi dan iklan kedepannya.
Sebagai penutup; dalam beberapa hal, menulis menjadi jalan terbaik dalam mengekalkan sebuah karya visual, termasuk fotografi dalam iklan. Tanpa ditulis, foto hanya akan serupa ucapan yang terimbun ucapan-ucapan baru. Meriah namun dilupakan. Tanpa berlindung pada metafor: biarkan foto yang berbicara, kajian dalam buku ini mencoba terlepas dari metafor tersebut, karena tak ada foto yang “benar-benar” bisa bicara. Namun, melalui materi visual yang termuat di dalamnyalah kita bisa membicarakan sebuah foto dengan ragam perspektif, seperti yang terangkum dalam buku ini. Ia (foto) memang tak bisa bicara, namun selalu bisa dibicarakan. Salam.
*Tulisan ini digunakan sebagai modal diskusi buku “Retorika Visual Fotografis dalam Iklan Koran” Karya Prayanto W.H. (Yogyakarta: Kanisius, 2016). Di selenggarakan di FSR ISI 5 Oktober 2016
Karena Desain Komunikasi Visual adalah Keseharian*
“Profesi desainer komunikasi visual menjadi bagian dari mata rantai sebuah penelitian sosial. Desainer komunikasi visual, sebelum berkarya haruslah melakukan berbagai kajian dengan pendekatan lintas ilmu” (Sumbo Tinarbuko, 2015)

DEKAVE Desain Komunikasi Visual Penanda Masyarakat Global (Sumbo Tinarbuko:2015)
Jika Anda pernah menyaksikan # (hastag, tanda pagar) manusia setengah Sumbo, maka Anda sedang bersinggungan dengan buku “DEKAVE Desain Komunikasi Visual-Penanda Zaman Masyarakat Global”. Sebelum membincang isi buku, saya ingin memulai perbincangan dari halaman sampul. Melalui sampul, Sumbo mencoba memosisikan dirinya “tak utuh”. Setengah. Tentunya bukan dalam artian sesungguhnya. Ia coba merepresentasikan perspektif, perspektif masyarakat desain komunikasi visual. Setengah dari kreator, setengah lagi dari para konsumen. Sampai titik ini mungkin Anda sudah paham apa yang saya maksudkan. Ya, secara kewacanaan karya dan pemikiran desain komunikasi visual tidak pernah “utuh” sebelum sampai ke publik, ia tidak pernah benar-benar menyatu sebelum sampai titik sasarnya. Maka dari itu, -selanjutnya- publiklah (masyarakat global) yang kemudian “menggenapi” pemaknaan dari sebuah karya desain. Ada produsen ada juga konsumen, dan di tengahnya hadir praktik kewacanaan. Bukankah dalam proses komunikasi selalu membutuhkan dua ruas tersebut, produsen dan konsumen? Tentunya materi visual dalam sampul buku ini bisa diperbincangkan lebih jauh.
Sebagai bagian dari “masyarakat” Dekave, saya coba memahami “DEKAVE Desain Komunikasi Visual-Penanda Zaman Masyarakat Global karya Sumbo Tinarbuko (2015) sebagai sebuah arena yang menarik. Setidaknya kita bisa membagi buku ini ke dalam dua ruas. Yang pertama, ia mengarah ke dalam (masyarakat DKV) dan yang kedua ia mengarah ke luar (masyarakat global). Yang pertama dapat diartikan sebagai catatan tentang diri, tentang DKV sebagai institusi “sosial”. Bagaimana secara institusional DKV berperan dalam upaya membimbing mahasiswa agar memiliki kemampuan sebagai calon desainer komunikasi visual yang mampu mengemukakan konsep berpikir, menganalisis, merancang desain berdasarkan kaidah estetika (Tinarbuko, 2015: 85).
Perbincangan menyangkut diri (masyarakat DKV) bukan saja menyangkut kurikulum pendidikan, tapi juga bagaimana pola-pola perancangan desain yang terus dituntut cepat dan “kekinian”. Di era media siber saat ini, “cepat” dan “kekinian” adalah dua kata yang terus didengungkan sebagai ujung tombak. Secara tak langsung, selera pasar telah membangun konstruksi apa yang disebut dengan “kekinian”. Saya pikir, memahami selera bukanlah sesuatu yang sederhana. Riset dan amatan-amatan sosial mutlak diperlukan.
Dan di sinilah kemudian Desain Komunikasi Visual, selanjutnya saya tulis DKV –mau tak mau- harus bersinggungan dengan ruang-ruang sosiokultural yang terkait dengan fenomena sosial. Selain itu, seperti misalnya dalam “Mendongkrak Gairah Wacana Desain Komunikasi Visual” (hlm: 12), bab ini menawarkan perbincangan yang menarik, bagaimana karya desain bukan saja dituntut kreatif dan baru, tapi juga dituntut menjadi sebuah karya yang memberikan perspektif yang baru, solutif juga mendidik.
Masih dalam bab yang sama, saya coba kutipkan:
“jika karya desain grafis dan desain komunikasi visual bisa diangkat ke singgasana yang lebih terhormat, maka di sisi kiri dan kanan keberadaanya perlu dilengkapi pula dengan bentuk publikasi ilmiah artikel, kajian populer di sejumlah media massa guna menginformasikan kepada masyarakat perihal fungsi dan peran desain grafis atau desain komunikasi visual tersebut.
Sebab perkembangan ilmu desain grafis atau desain komunikasi visual tanpa dukungan dan partisipasi aktif para pihak sulit bisa dilaksanakan. Jika hal tersebut terus berlangsung, maka keberadaan desain grafis dan desain komunikasi visual sebagai salah satu kajian kebudayaan akan jalan di tempat alias mandheg!”
Dan yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh apa kita menulis tentang Desain Komunikasi Visual?
Buku ini bisa menjadi “tonggak” dalam melihat diri, tentang DKV dalam hubungannya dengan masyarakat. Salah satu yang kemudian terbersit dalam benak saya adalah kajian-kajian yang melibatkan massa, dengan kata lain kajian audiens. Sebagai arena multidisiplin, dalam penyajiannya, DKV selalu melibatkan masyarakat global. Selain itu, ketika perkembangan teknologi dan tata pola kehidupan masyarakat terus berkembang maka pengkajian dengan ragam disiplin harus mulai dikembangkan. Saya rasa, masih banyak “ruang kosong” dalam pengkajian karya DKV. Dan tentunya harus mulai digarap dan dimeriahkan. Mau tak mau. Dan tentu saja hasil kajian-kajian tersebut bisa menjadi modal dalam penciptaan. Di antara keduanya bisa saling melengkapi sekaligus menguatkan.
Setiap hari kita berhubungan dengan karya-karya DKV, hampir semua indra kita merasakan citraan yang dihadirkan. Entah di rumah, jalanan, maupun di pusat perbelanjaan. Sebagai khalayak aktif, tentunya kita selalu membangun pemaknaan-pemaknaan dalam melihat karya-karya yang ada.
Karena estetika saja tidak cukup. Mengingat yang kedua, DKV mengarah ke luar sebagai produk sekaligus memosisikan diri sebagai “konsumen”. Konsumen dalam artian, DKV mengonsumsi realitas sosial yang kemudian dihadirkan kembali dalam bentuk karya desain, lantas kemudian menghadirkan karya tersebut kepada khalayak. Dan khalayak kemudian meresponnya (kembali) dengan caranya masing-masing. Begitu seterusnya. Seperti yang banyak diulas dalam bagian buku ini perihal iklan. Iklan dan ruang publik menjadi isu yang terus muncul bagi masyarakat perkotaan. Tata ruang kota dan keberadaan iklan perlu ditilik kembali. Pun dengan hubungan antara masyarakat DKV dengan masyarakat global yang keduanya bukan saja dihubungkan oleh rantai industri namun juga pada produksi karya yang edukatif, etis, juga estetis.
Ruang kota adalah ruang yang plural. Di dalamnya tumbuh ragam ideologi, juga kebudayaan yang melibatkan fenomena-fenomena sosial. Menyepakati apa yang diutarakan oleh Sumbo Tinarbuko bahwa pengkajian DKV dalam konteks lintas ilmu perlu ditunjang; ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu hukum humaniora, semiotika, dan lainnya (Tinarbuko, 2015:117).
Sebagai penanda zaman, karya DKV bukan hanya melibatkan desainer, karya, dan industri, tapi juga melibatkan masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon dan memaknai desain komunikasi visual. Perbincangan dalam buku ini menarik untuk terus disimak dan bisa dijadikan modal dalam melihat perkembangan DKV kedepannya. Tentunya pengkajian bukan saja bagian dari melihat dan mengamati, namun juga menjadi modal bagi “pencipta” desain. Karena desain komunikasi visual adalah keseharian, di mana sehari-hari kita terlibat dan melibatkan diri dalam proses-proses penandaan, merespon apa yanag dihadirkan oleh para desainer komunikasi visual. Menjadikannya sebuah penanda zaman (meminjam istilah Sumbo Tinarbuko) dan tentu saja dalam keseharian kita perlu tahu kebutuhan juga perlu paham seperti apa kebutuhan itu dihadirkan. Jika berlebihan? Ya hasilnya seperti yang kita saksikan di ruas ruas jalan perkotaan. Terakhir sebagai penutup: Salam Merdekave!
*Dengan sedikit tambahan, dan sedikit perubahan. Sebelumnya tulisan ini pernah sebagai “modal” diskusi buku DEKAVE Desain Komunikasi Visual-Penanda Zaman Masyarakat Global. Karya Sumbo Tinarbuko (Yogyakarta: CAPS, 2015). Di selenggarakan di DKV, FSR ISI Yogyakarta 8 Desember 2015.
Menonton Pameran Foto: Mencatat Kisah dan Drama dari Panggung Laut.
Mengawali catatan ini saya teringat H.F Tillema, ahli obat asal Semarang yang juga dianggap sebagai bapak pendiri fotografer modern Hindia Belanda. Dalam uraian yang disampaikan Mrazek (2006), Tillema menyusun Kromoblanda yang penuh dengan foto-foto. Ia membuat foto, menggolong-golongkan, dan menyimpan foto tersebut disemacam daftar “pusat foto”. Kromoblanda tersebut dimaksudkan sebagai “catatan perjalanan”.
Mrazek dalam Engineers of Happy Land; Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni berujar “dua mata sering tidak cukup untuk mengawasi mereka”, (2006: 145). Maka bolehlah jika kemudian saya memaknai bahwa fotografi selain berfungsi sebagai media rekam juga menjalankan fungsinya sebagai “pengawasan”, dengan kata lain: kontrol sosial hadir di dalamnya. Bukankah dengan melihat foto, kita tidak sekadar menyaksikan, namun juga memaknai akan hadirnya objek foto. Termasuk apa yang kita rasakan ketika mengunjungi sebuah pameran (foto).
Memindahkan objek ke dalam foto adalah upaya dalam membentuk realitas. Menghadirkan citraan, juga membangun hubungan subjek-objek, antara yang memotret dan yang dipotret. Jika mengunjungi pameran foto adalah sama halnya dengan tamasya dalam perpustakaan visual, maka di dalamnya kita akan mendapatkan data visual dari perjalanan para fotografer. Pameran foto Nusa Bahari yang digelar 1-9 September 2015 di Bentara Budaya Yogyakarta menghadirkan kisah laut dengan rupa-rupa drama di dalamnya. Laut memang panggung drama. “Berupa-rupa drama terjadi di atas panggung laut. Drama pengungsi rohingnya misalnya”, seperti kata Sindhunata dalam pengantar pameran.
Kita bisa menemui 165 lembar foto yang terpasang rapi di masing-masing sudutnya. Termasuk apa yang disinggung Sindhunata dalam pengantar pameran tersebut, pengungsi Rohingnya. Bagi mereka, laut bukan sekadar panggung, laut adalah jalan. Laut seakan adalah “jalan tol” yang boleh mereka tempuh untuk membebaskan dirinya dari segala penderitaan, penistaan yang mereka alami di negerinya sendiri. Laut adalah sarana yang disediakan alam bagi mereka untuk mencari kebebasannya (Sindhunata, 2015).
Anak-anak Rohingnya ditampilkan sebadan penuh. Dengan atribut papan nama serta berlatar angka-angka penunjuk tinggi badan. Tak ada foto yang melihatkan perjalanan mereka, pun tak ada foto yang menghubungkan mereka dengan laut. Tanpa adanya teks pendamping, mungkin saja kita akan terjebak pada tafsiran yang aneka rupa, jauh dari maksud. Untungnya, kehadiran teks (keterangan foto) pada foto jepretan Ulet Ifansasti ini telah memberikan jalan dalam menafsir foto.
Ulet, dalam salah satu keterangan fotonya menuliskan: “pengungsi Rohingya, berpose saat menjalani proses identifikasi di tempat penampungan sementara di Kuala Langsa, Aceh (18/5/2015). Ratusan pengungsi Rohingnya tiba di Indonesia pada 15 Mei 20015 dan mereka membutuhkan layanan kesehatan. Ribuan pengungsi lainnya diperkirakan masih berada di lautan karena sejumlah negara tidak bersedia menampung mereka. Komunitas Muslim Rohingnya di Myanmar sudah sejak lama dimarjinalkan oleh sebagian besar masyarakat Budha negara tersebut”. Di sinilah kekuatan teks, seperti yang disebut Hall (1973) sebagai a preffered reading. Kata-kata sebagai materi historis berdaya mengarahkan sekaligus membimbing kita menuju pada makna foto.
Dari 10 foto yang ditampilkan, delapan di antaranya menghadirkan sosok anak-anak tanpa orang lain di sampingnya. Polos, sedikit senyum dengan kedua tangan memegang papan informasi yang berisi kolom nama, umur, pekerjaan, dan juga alamat. Jika pekerjaan seseorang adalah simbol kepemilikan kapital yang bisa diartikan secara politis melibatkan kelas (sosial), maka dengan menampilkan pose anak-anak dengan segala keluguan dan kepolosannya mampu mereduksi “keterlibatan” kelas dalam foto-foto tersebut. Ada yang menarik untuk ditilik lebih jauh, dalam foto Syohid (2 tahun), ia menangis meronta dalam gendongan, sedang perempuan yang menggendongnya penuh tatapan kosong memegang papan identitas yang diberikan petugas.
Komposisi semacam ini memang memiliki kesan lebih sederhana jika dibandingkan foto berkategori “human interest” lainnya. Saya mengamini apa yang pernah diutarakan Barthes, sesederhana apapun sebuah foto, Ia seperti menghadirkan sebuah kebenaran, kebenaran akan sebuah kehadiran. Dan kehadiran dalam hal ini tidaklah alamiah, namun ada pembentukan, ada konstruksi dan ada relasi ruang antara fotografer dan objek foto. Bagaimana medium fotografi dijalankan untuk memperoleh data visual para pengungsi.
Galeri Nusa Bahari terbangun atas beberapa fragmen. Terbangun “Sekilas misteri, kisah, dan drama kehidupan dari laut”, seperti yang dituliskan Sindhunata sebagai judul pengantar pameran. Selain rentetan foto anak-anak Rohingnya, masih ada 155 foto lain yang menarik untuk di simak. 155 foto tersebut terbagi dalam 31 fragmen yang coba dikisahkan, mengenai: Anak Pantai, Belah Kapal, Biota Bawah Laut, Hiu, Hut RI, Ibadah Laut, Kampung Tenggelam, Kapal Pinisi, Mangrove, Bumi Gora, Pantai Timur Indonesia, Pemandangan Laut, Pembuatan Kapal, Pulau Komodo, Reklamasi, Dampak Bencana Laut, Sand Boarding, Surfing Pantai Selatan, Tentara Pertahanan, Terumbu Karang, Tuan Ma, Biota Sekitar Laut, Tumpahan Minyak, Ubur-ubur, Wanita, Wisata, Nelayan, Sedekah Laut, Olahraga Bahari, dan Suku Lingga
Dari sekian banyak foto yang dipajang, ada satu foto yang cukup menarik untuk diperbincangkan, foto “Anak Pantai” karya Agung Kuncahya (Xinhua). Jika Anda memasuki ruang pameran, maka Anda akan menemui foto tersebut di baris-baris awal. Penempatan ini cukup berhasil dalam membangun konstruksi tentang drama kehidupan laut. Tentu saja ini menyangkut psikologi penonton foto, bahwa penampakan (visual) yang pertama kali diamati akan berpengaruh pada pengamatan-pengamatan selanjutnya. Cukup lama saya berada di depan foto tersebut, sambil sesekali mengingat apa yang ditulis oleh Sindhunata dalam pengantarnya.
Selain mengabadikan momen sebagai data visual, fotografi juga mampu menciptakan momen. Karena apa yang ditangkap oleh kamera bukanlah sesuatu yang alamiah. Ada pengonstruksian, pose-pose yang tercerai dengan objeknya, seperti kata Barthes bahwa ketika seseorang berpose di depan kamera maka ia membuat tubuh lain bagi dirinya, menderita ketidakotentikan, karena diri dan citra-diri diceraikan oleh fotografi.
Dengan format hitam putih, foto tersebut menggambarkan sosok gadis kecil berambut sebahu, duduk di atas tatanan bambu yang menjorok ke laut, di dekatnya ada bambu berukuran agak besar menjulang tepat di atas pelipis matanya. Pandangan mata menerawang jauh, terlihat kosong. Mungkin bisa ditafsir: ada angan dan harapan tentang kehidupan mendatang sebagai anak pantai. Dalam keterangannya, Agung menjelaskan bahwa foto tersebut diambil di pinggir pantai yang tercemar, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, 2012 silam. Selain mengarahkan pada proses pemaknaan, teks -dalam bahasa Barthes- juga berfungsi sebagai “pengait” yang secara sederhana memberikan acuan kepada kita foto tentang informasi-informasi dalam foto.
Kesan apa yang kemudian kita dapat dalam melihat format hitam putih yang ditawarkan Agung? Akan banyak jawaban, dan yang paling lumrah, –mungkin- kita akan menjawabnya “agar lebih dramatis”. Keterhubungan foto dengan teks yang menyertainya amatlah erat, seperti parasit. Menempel dan berpengaruh. Di jelaskan bahwa foto tersebut “bercerita” tentang wilayah pantai yang tercemar. Lebih jauh, citraan format hitam putih dengan sedikit “grain” bisa diasosiasikan sebagai perwujudan kawasan yang tercemar. Kita bisa membayangkan jika format foto tersebut berwarna, dengan langit yang membiru dan awan yang menggurat halus. Akan ada kesan segar. Maka jelas, dalam sifatnya (foto) yang polisemi, teks mampu memberikan acuan mengenai informasi serta mengarahkan dalam proses pemaknaan.
Tak jauh dari anak perempuan tersebut, beberapa anak laki-laki bersuka ria mandi di pantai, melompat dengan riangnya. Ada dua ekspresi yang saling berlawanan: antara yang kosong dan yang ceria. Mereka yang bersuka ria melompat sembari menghadap kamera, ada “eksyen”, objek menjadi tak lugu lagi. Sebagai media (visual), fotografi mampu membentuk objek sedemikian rupa sesuai kehendak fotografer untuk membangun penceritaan. Dan inilah drama dari panggung laut. Ada keceriaan, ada tatapan, dan ada juga kisah yang dihadirkan.
Akhir kata, bolehlah jika saya berpendapat bahwa dalam ruang pameran ini ada catatan tentang kebaharian. Catatan tentang laut beserta ragam yang terkandung di dalamnya. Dan yang kemudian menarik ditunggu adalah keberlanjutan dari catatan (visual) ini. Apakah hanya akan berhenti sebagai catatan –saja- atau akan ada langkah-langkah strategis menyangkut kebaharian kita.



Komentar Terbaru