Memoar Fotografis: Memperbincangkan Retorika Visual Fotografis dalam 44 Tahun
karena tak ada foto yang “benar-benar” bisa bicara. Namun, melalui materi visual yang termuat di dalamnyalah kita bisa membicarakan sebuah foto dengan ragam perspektif.
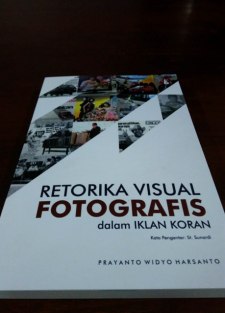
Rentang waktu 44 tahun menjadi rentang yang cukup panjang dalam memperbincangkan fotografi dan iklan. Jika biasanya memoar mengacu pada catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang, maka tidak dengan catatan ini. Catatan ini sengaja saya beri judul “memoar fotografis” dengan pertimbangan bahwa buku ini melibatkan peristiwa fotografis iklan koran dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dimulai dari iklan cetak pertama di Surat Kabar Kompas (1965) hingga 2009. Baik iklan maupun fotografi, keduanya sama-sama berangkat dari fenomena sosial. Secara sosiokultural keduanya bisa dikatakan sebagai bentuk respon kebutuhan, baik kebutuhan industri maupun kebutuhan masyarakat.
Ada 437 iklan yang menjadi amatan Prayanto W.H, penulis buku ini (baca: Retorika Visual Fotografis dalam Iklan Koran). Jumlah yang banyak, bahkan dapat dikatakan sangat banyak. Selama periode tersebut, iklan-iklan dikategorikan. Kategorisasi tidak sebatas pada bab kerja-kerja mekanis, namun juga hal-hal politis dalam fotografi.
Sebagai arena multidisiplin, fotografi dalam berbagai bidang (termasuk fotografi dalam iklan) bisa dibicarakan dengan ragam keilmuan. Yang kemudian menarik untuk diperbincangkan di awal adalah perihal persinggungan fotografi dengan industri. Sejak awal kemunculannya, fotografi menjadi salah satu bentuk penemuan yang cukup penting dalam merespon kebutuhan manusia dan industri. Terlebih lagi, ketika fotografi ditemukan dan dipatenkan pada 1839, di Eropa sedang terjadi Revolusi Industri. Dimana alur perdagangan kian padat, dan pabrik-pabrik semakin bermunculan. Dan fotografi muncul sebagai salah satu kekuatan visual (baru) dalam merespon tumbuh kembangnya industri pada waktu itu.
Menyoal Retorika Visual, merujuk tulisan Matthew Rampley dalam Exploring Visual Culture (2005) yang berjudul Visual Rhetoric. Di katakan bahwa Retorika visual memiliki peran penting dalam melihat budaya visual dalam kaitannya dengan mekanisme sosial dan ideologi. Dalam salah satu sub babnya: Visual Communication and Visual Rhetoric, Rampley “meminjam” salah satu esai Barthes yang membahas sampul majalah Paris Match. Sampul tersebut menampilkan seorang prajurit kulit hitam dengan seragam militer Prancis sedang memberi hormat kepada Bendera Prancis. Esai ini digunakan untuk menjelaskan relasi (kuasa) antara produk visual dengan struktur sosial yang ada. Visual semacam ini memiliki daya “politis” dalam membangun opini serta membangun “kesadaran” audiens. Pun dalam bahasan ini (fotografi iklan). Iklan melalui fotografi dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga mampu membangun tawaran yang “ideal” mengenai kehidupan. Tawaran “ideal”, atau lebih jauh bisa dikatakan seolah-olah “ideal”. Kata ideal sengaja saya kasih tanda petik, karena “ideal” tentu saja bukan sesuatu yang serta-merta muncul dalam benak konsumen, tapi melalui proses pemaknaan yang kompleks. Ada relasi kuasa antara Industri (pembuat iklan) dan (calon) konsumennya.
Sependek yang saya tahu, tak banyak buku-buku yang membincangkan fotografi dari sisi wacana kritisnya. Kebanyakan hanya berpijak pada persoalan teknis. Dan tak banyak para mahasiswa yang mengambil tugas akhir bab fotografi mau mengalih mediakan dari format akademis (skripsi-tesis-disertasi) ke dalam format buku yang lebih lentur. Buku yang sedang kita bahas ini merupakan “alih format” dari disertasi ke dalam bentuk buku, dan menjadi salah satu dari yang sedikit tersebut. Hal ini tentu saja membawa angin segar dalam perbincangan fotografi yang “hampir selalu” berorientasi dalam persoalan teknis.
Secara pragmatis, fotografi dalam iklan berfungsi untuk mempengaruhi konsumen, namun dalam keparagmatisannya ada sesuatu yang politis. Bukan hanya sekadar mendaya fungsikan kemapanan estetika, namun ada “tawaran ideal” bagi kehidupan sosial. Di sinilah kemudian fotografi mampu membangun konstruksi aneka rupa kode sosial mengenai sesuatu yang “ideal”. Nilai-nilai “ideal” tersebut kemudian –dalam bahasan ini, salah satunya- diperantarai melalui figur tokoh sebagai pembawa pesan.
Setidaknya ada dua hal yang menarik untuk kita perbincangkan dalam buku ini, yang pertama menyoal kekuatan fotografi dalam mengkonstruksi realitas, baik dari segi teknis maupun wacana (materi) visualnya. Yang kedua: mengenai citra-citra periklanan di setiap periodenya. Penulis membagi tiga periode dalam kajiannya. Dan masing-masing periode menunjukan gaya visual serta wacana yang berbeda. Tidak semua bab akan saya bicarakan dalam ulasan kali ini, hanya beberapa saja. Terutama bagian-bagian yang mengacu pada gaya fotografi dan wacana-wacana (politik) fotografis. Meski tidak menutup kemungkinan bagian-bagian lain bisa saja disinggung, karena pertautan dalam masing-masing bab bisa dibicarakan secara mandiri maupun secara bertaut.
Tiga periodisasi masa dalam buku ini; yang pertama periode 1965-1970an. Pada periode ini iklan-iklan menggunakan kekuatan visual fotografi untuk membangun citra produk. “gaya informasi iklan bersifat informasi yang berorientasi pada produk” (hlm: 98). Beberapa di antaranya: Iklan pertunjukan musik The Trolls Quartet (10 September 1965), Iklan Corned Beef Chips (23 Juni 1967), dan Iklan Electone merek ‘Yamaha’ (27 Juni 1976). Jika dilihat dari visualnya, pada lapisan lebih dalam, Iklan-iklan pada periode ini selain berorientasi pada produk juga membawa tawaran mengenai gaya hidup. Ada konstruksi identitas yang diprasaranai oleh pakaian. Juga ada “identitas” figur yang didayakan untuk mendongkrak pemasaran. Misalnya pada iklan Corned Beef Chips, terdapat teks yang secara jelas mengacu pada hidangan “saya selalu memakai CIP Corned Beef & Sopini untuk membuat bermacam-macam hidangan yang lezat” (hlm: 104). Dengan bintang iklan Ny. Tanzil yang mengenakan sanggul dan kebaya. Ini menarik, bagaimana hidangan “ala barat”, namun dalam iklan disajikan oleh seorang yang bersanggul dan berkebaya yang notabene “corak budaya timur”. Ada semacam “permainan” identitas dalam iklan tersebut.
Selanjutnya pada periode kedua: 1980-1990-an, ada citra diri yang difungsikan sebagai kekuatan iklan. Citra beserta identitasnya dikonstruksikan sebagai pola wicara dalam iklan. Beberapa iklan yang menjadi ulasan dalam periode ini: Iklan Sabun Lux ( 9 maret 1978), Iklan televisi ‘Grundig’ (22 Januari 1980), Iklan Rexona ( 6 Juni 1980), Iklan Mobil ‘Kijang’ (10 Desember 1986) dan iklan Mobil Mazda (11 November 1995). Permainan metafor (visual) terlihat dalam periode ini. Teks didayakan untuk membangun imaji yang ideal. “ Saya pertama kali mengenal LUX di Paris”, Teks ini muncul dalam Iklan Lux. Tampilan foto seorang wanita berdandan ala wisatawan, dengan latar belakang Menara Eiffel. Modis. Sesuai dengan apa yang selama ini diidentikan dengan Paris sebagai kota yang modis. Selanjutnya, pada Iklan Rexona: “Akhirnya dia yakin berkat Rexona”. Visualisasi sepasang –mungkin- kekasih, berdiri berdekatan dengan perempuan sedang asik dan lelakinya terlihat melirik dengan senyuman kecil.
Periode ketiga; pasca 2000an, gaya visual iklan mulai bergeser pada ekspresi pengalaman pengguna. Secara sosial, ekspresi pengalaman masyarakat didayakan dan dijadikan sebagai strategi dalam konstruksi visual iklan. Seperti terlihat pada Iklan Sepeda Motor ‘Dast’ ( 1 November 2000), Iklan pendingin ruangan merek Sharp (24 Juli 2009), Iklan Flexi (13 juni 2009) dan Iklan Handphone Samsung (13 Mei 2002).
Dari rangkaian data dan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa visualisasi fotografis dalam iklan menjadi representasi kehidupan industri dan kehidupan masyarakat (konsumen) yang berorientasi pada tawaran “ideal”. Buku ini cukup komplit dalam membincang fotografi dalam iklan, tapi bukan berarti lantas menutup kemungkinan untuk membicarakan hal yang sama (fotografi dalam iklan). Karena ketika sebuah objek sudah atau sedang diperbincangkan, sekomplit apapun, tentunya akan terus melahirkan turunannya, celah-celah itu tetap tersedia dan perlu untuk terus diisi. Dan di sinilah menariknya. Ketika teknologi makin berkembang, terlebih lagi dengan kehadiran ruang media baru, fotografi dengan gaya visualnya pun terus berkembang. Tentu saja kehadiran buku ini bisa menjadi semacam alat berpijak dalam melihat fenomena fotografi dan iklan kedepannya.
Sebagai penutup; dalam beberapa hal, menulis menjadi jalan terbaik dalam mengekalkan sebuah karya visual, termasuk fotografi dalam iklan. Tanpa ditulis, foto hanya akan serupa ucapan yang terimbun ucapan-ucapan baru. Meriah namun dilupakan. Tanpa berlindung pada metafor: biarkan foto yang berbicara, kajian dalam buku ini mencoba terlepas dari metafor tersebut, karena tak ada foto yang “benar-benar” bisa bicara. Namun, melalui materi visual yang termuat di dalamnyalah kita bisa membicarakan sebuah foto dengan ragam perspektif, seperti yang terangkum dalam buku ini. Ia (foto) memang tak bisa bicara, namun selalu bisa dibicarakan. Salam.
*Tulisan ini digunakan sebagai modal diskusi buku “Retorika Visual Fotografis dalam Iklan Koran” Karya Prayanto W.H. (Yogyakarta: Kanisius, 2016). Di selenggarakan di FSR ISI 5 Oktober 2016

Terima kasih sudah menulis, Mas Daru. Kita perlu bacaan, opini, atau jurnal fotografi. Blog ini bisa jadi oase. Salam